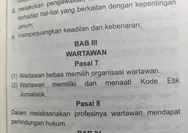Menurut Mahfud MD (2011), moral dan etika hukum Indonesia saat ini justru memunculkan mafia pengadilan yang memainkan undang-undang dan konstitusi. Padahal hukum dibentuk oleh kristalisasi nilai moral dan etika di masyarakat. Akibatnya, hukum bisa dipermainkan, bisa diatur oleh mafia peradilan. Bobroknya hukum akibat permainan seperti itu, ada di semua lini. Pelanggaran hukum hanya ditindak berdasarkan aturan formal dan legal dalam undang-undang. Dalam penuntutan, pasal yang digunakan bisa dimainkan pengacara, jaksa, hingga hakim. Hukum legal bisa dimainkan.
Pada artikel berjudul “Hukum Sebagai Permainan dan Alat Penaklukan?” (26/10/2020) saya tegaskan bahwa permainan hukum, rekayasa hukum, atau apapun penyebutannya (termasuk pemelintiran hukum), merupakan pelanggaran moral, etika, dan agama. Keseluruhannya dilarang.
Baca Juga: Presiden Jokowi isyaratkan pandemi Covid-19 segera berakhir, ini tandanya
Walau demikian, tidak bisa dipungkiri, sebagai sisa-sisa warisan penjajahan Belanda atas negeri ini, masih banyak perundang-undangan di Indonesia berwatak liberal-individual. Civil law system atau tradisi hukum Eropa Daratan, masih terasa dominan. Dipraktikkan dalam berbagai persoalan bangsa. Tradisi hukum ini senantiasa menempatkan para elit – politikus, pebisnis, oligarki, polisi, militer, buzzerRp, influencer, dan sejawatnya – pada puncak kehidupan bernegara. Merekalah yang berkuasa. Merekalah yang membuat kebijakan, membuat hukum, melaksanakan, dan sekaligus mengendalikan penegakan hukum. Tiadalah hukum dipandang sah kecuali hukum negara. Undang-undang adalah produk politik.
Dengan kata lain, aktivitas-aktivitas apapun, hanya dipandang sah bila sudah dilegalkan oleh penguasa. Pelegalan itu dimulai dari atas, melalui enacted atau legislated law. Melalui metode top down dan represif. Maka, hukum dengan cepat diberlakukan pada semua aspek kehidupan.
Tradisi hukum ala kolonial/penjajah tersebut pada satu sisi efektif dan efisien bagi para elit. Namun demikian, pada sisi lain, yakni pada rakyat, dirasakan sebagai penaklukan. Hak-hak rakyat dirampas. Hak-hak dimaksud mencakup: hak berpendapat, hak berkumpul, hak atas upah buruh yang layak, hak atas sumber-sumber kehidupan (atas tanah, air, tambang, lingkungan dan sebagainya).
Tradisi hukum ala kolonial menempatkan kedaulatan hukum pada penguasa. Bukan pada rakyat. Bahkan sampai pada pengkategorian, penguasa itu subjek hukum, sementara rakyat itu objek hukum. Inilah berbagai bentuk pemelintiran hukum yang semakin marak.
Dengan penjelasan di atas, kiranya dapat dipahami, betapa kecewa dan masgul Pak Kiai terhadap realitas empiris kehidupan bernegara hukum di negeri ini. Lantas bagaimana solusinya? Sangat diharapkan para ulama, akademisi, budayawan - utamanya yang masih komitmen pada moral – bersinergi, berkontribusi, dan memikirkan masalah ini secara serius. Wallahu’alam
*)Penulis, Guru Besar Ilmu Hukum UGM