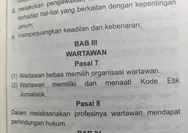Oleh: Sudjito Atmoredjo*)
“Dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati siapa tahu”. Peribahasa ini telah dikenal masyarakat luas. Dua realitas, yakni: laut dan hati, diperbandingkan. Jelas beda. Sungguh tidak rasional. Apa pesan moral dari peribahasa ini? Apa pula kaitannya dengan hukum?
Pada ranah filsafati, laut adalah materi-duniawi. Betapapun luas dan dalam, laut bisa diukur. Dapat diketahui seberapa luas dan dalamnya. Hal demikian, berlaku untuk materi-materi lain. Misal, gunung itu tinggi. Seberapa ketinggiannya, dapat diukur. Jarak satu kota ke kota lain, berapa kilometer? Dapat dipastikan setelah diukur. Berat seekor gajah, berapa koligram?
Dapat dipastikan setelah ditimbang. Perkembangan ilmu dan teknologi, lengkapnya sarana-prasarana, amat membantu terjawabnya pertanyaan-pertanyaan tentang berbagai materi-duniawi.
Baca Juga: HUT Bhayangkara ke 77, Polres Sukoharjo lakukan anjangsana ke purnawirawan Polri
Berbeda halnya dengan hati. Pada ranah spiritual-religius, hati disebut qalbu. Apa qalbu? Secara umum, qalbu adalah aspek terdalam dari jiwa manusia. Itulah perangkat kejiwaan, yang berfungsi sebagai alat ukur terhadap benar atau salahnya perasaan, niat, angan-angan, pemikiran, hasrat, sikap dan tindakan seseorang, terutama dirinya sendiri.
Imam Al-Ghazali, mengartikan qalbu dalam makna substansial, sebagai: nurani, ruhani. Berposisi dalam satu kesatuan pada diri manusia hidup. Qalbu sebagai substansi berifat lembut. Itulah perilaku otentik manusia.
Untuk menjelaskan keterkaitan peribahasa di atas dengan hukum, dikemukakan kisah imajiner berikut. Ada seorang (sebut: Abu Waras), berkeinginan membersihkan diri dari noda dan dosa. Berjalanlah dia menuju laut. Dicarilah tempat sepi. Bebas dari tatapan manusia. Di sanalah, air melimpah. Bisa mandi sepuas-puasnya. Hingga dirinya betul-betul bersih.
Terbayangkan, usai mandi, kebugaran jiwa-raga akan kembali pulih.
Sesampai di pinggir laut, dijumpai laki-laki duduk di atas batu. Dilemparkanlah olehnya genggaman-genggaman garam ke laut. Melihat kejadian itu, prasangka buruk (suudzon) merasuki jiwa Abu Waras. “Sungguh. Orang itu bodoh. Berbuat sia-sia. Bukankah laut sudah asin. Mengapa digarami?!”. Beralihlah Abu Waras ke tempat lain.
Sesampai di teluk, ada seorang melemparkan bongkahan-bongkahan gula ke laut. Abu Waras kembali berprasangka buruk. “Tampaknya, ini juga orang bodoh. Mana mungkin air laut diubah menjadi manis”. Segera ditinggalkan. Dicari tempat lainnya.
Di suatu pantai, dijumpai seorang melemparkan ikan mati ke laut. Kata hati Abu Waras, “Walau laut itu rumahnya ikan-ikan, mana mungkin, ikan mati dilempar ke laut dapat hidup kembali. Orang ini bodoh juga”. Segera ditinggalkan. Perjalanan berlanjut.
Tiba-tiba ombak besar menerjangnya. Abu Waras jatuh, tertelungkup. Basah kuyup. Tak berdaya. Terpikirkan olehnya, walau di sini tak ada orang lain, tetapi mandi di laut lebih baik diurungkan. Ombak lebih besar, dapat menyeretnya, hingga tenggelam di laut.
Sebelum kembali pulang, Abu Waras, duduk merenung di atas tonggak kayu. Jiwanya, gundah, berkecamuk. Berbagai hal dipertanyakan pada diri sendiri. Jawabannya, akan menjadi referensi pembelajaran bagi semua orang.
Pertama, mengapa kehidupan ini misterius? Dalam keheningan, ada pengakuan, dirinya selama ini congkak, sombong, angkuh, sok serba tahu. Sikap demikian, menghalangi tabir kebenaran. Baru melihat bagian sedikit dari suatu kejadian, sudah berani berpendapat dan bersikap. Mudah berprangsangka buruk terhadap orang lain (suudzon), tanpa ilmu yang cukup.