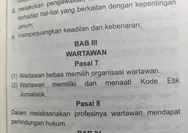Bayangkan seorang Victoria’s Secret Angel berdiri manis dalam antrean pengambilan PMT (Pemberian Makanan Tambahan) di kelurahan, menenteng kupon dua butir telur ayam mingguan. Surreal, tapi secara birokrasi sepenuhnya mungkin.
Masyarakat kita pun sigap membaca tubuh. Ibu-ibu kampung, dengan radar kasih sayang yang tak pernah salah arah, bisa langsung menjatuhkan rasa kasihan pada orang berperawakan kurus. Mereka tak peduli label fesyen; yang mereka pegang adalah logika sederhana: badan harus kuat, berisi.
Paradoks ini menunjukkan bahwa definisi kurus bukan angka netral. Ia dibentuk oleh budaya, kelas sosial, algoritma estetika, dan regulasi negara.
Padahal Badan Kesehatan Dunia (WHO) memandang kurus ekstrem sebagai kondisi yang membuka pintu risiko: anemia, tulang yang rapuh, hingga imunitas yang merosot. Di dalam negeri, Kemenkes mengkategorikan berat badan sangat rendah pada perempuan usia subur sebagai KEK atau Kekurangan Energi Kronis, sebuah status gizi yang menandakan tubuh bekerja dalam mode hemat darurat.
Baca Juga: Tawuran Nyaris Pecah Usai Final Piala Askab Sleman, Polisi Sigap Redam Ketegangan
Tubuh menjadi medan tarik-menarik antara prestise dan potensi masalah kesehatan. Dan di persimpangan itulah, kita mulai melihat bahwa kurus bisa menjadi pujian yang berkilau atau alarm yang menyala agresif—bergantung di negara mana kamu menimbang diri.
Kurus diurus negara
Begitu tubuh “kurus editorial” mendarat di tanah air, ia bukan lagi urusan estetika pribadi. Negara akan turun tangan dengan segala perangkat berikut program bantuan sosial.
Di Indonesia, tubuh kurus otomatis mengaktifkan jalur administratif pemerintah, bisa dari jalur Kemenkes atau Kemensos. Ada BLT gizi kurang atau bansos beras 10 kilogram. Ada pelatihan peningkatan nafsu makan yang diselenggarakan ibu-ibu PKK. Semua ini lahir dari niat baik negara untuk menolong sebagai intervensi nutrisi.
Bayangkan adegan ini: Bella Hadid berdiri patuh di Puskesmas, menunggu giliran timbang. Kader posyandu menegur lembut, “Mbak, sepatunya dilepas dulu biar akurat”. Lalu dokter berkata, “Enggak apa-apa, Mbak. Banyak kok yang begini. Yang penting rutin makan nasi”. Atau imbauan klasik: minum susu kental manis tiga kali sehari. Sebuah gagasan yang pernah dipromosikan sebagai sumber gizi, walaupun akhirnya direvisi karena produk dimaksud ternyata tidak mengandung susu. Dengan sketsa imajiner ini, tubuh selebritas dunia langsung tumbang di hadapan logika kesehatan ala Nusantara.
Baca Juga: Presiden Prabowo Tiba di Medan Pimpin Langsung Penanganan Bencana
Masyarakat ikut berperan. Ibu-ibu kampung menawarkan sayur sop, tetangga menyodorkan perkedel kentang, dan para bapak merasa wajib memberi ceramah singkat tentang pentingnya sarapan. Tubuh kurus diperlakukan seperti tamu negara yang harus segera disuguhi nutrisi, bukan biosfer estetika yang ingin dipertahankan pemiliknya.
Di perkampungan, anak-anak kurus menjadi aib bagi orang tua karena takut dikira tidak diberi makan yang cukup. Bila yang memiliki badan kurus adalah seorang wanita berstatus menikah, maka sang suami akan menjadi tersangka yang dianggap tidak mampu menyejahterakan istri.
Di tengah hiruk-pikuk ini, lahir satu kesimpulan lucu: tubuh kurus menjadi simbol sosial yang terlalu bernilai untuk dibiarkan netral. Ia bisa menjadi kebanggaan kelas menengah urban yang terpapar estetika global, namun dalam konteks lokal langsung berubah menjadi indikator rawan pangan. Maka muncullah istilah karangan kita: “Kurnut (kurang nutrisi) Global”—kelas menengah yang kurus bukan karena diet estetika, tapi karena tafsir budaya bertabrakan dengan standar gizi nasional.
Indonesia, dengan segala kehangatan dan keruwetan administratifnya, akhirnya menjadikan tubuh kurus sebagai ruang negosiasi identitas. Antara ingin tampil stylish dan dianggap sehat oleh negara, tubuh harus memilih: tampil seperti sampul majalah, atau lolos dari radar Kemenkes.